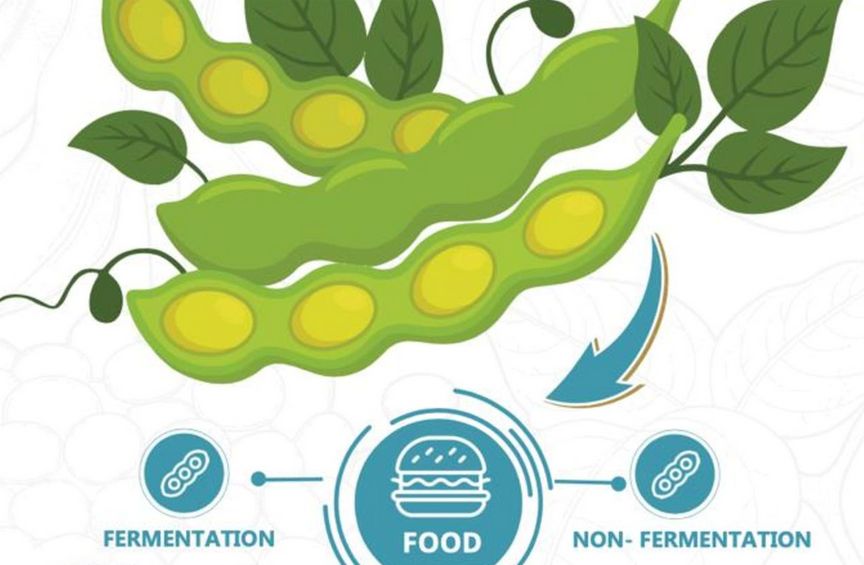Kedelai Lokal Non GMO yang Sehat untuk Anda
- Administrator
- Category: Artikel
- Hits: 272
Saekedelai UGM : Smart Enterprise Kedelai untuk Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal
- Gusti Grehenson
- Category: Artikel
- Hits: 319
Budaya mengonsumsi produk pangan olahan kedelai di Indonesia dapat terlihat dari makanan berupa tahu, tempe, kecap, dan tauco yang tersedia di meja makan telah menjadi menu sehari-hari bagi sebagian masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain rasanya yang enak, produk pangan ini mengandung gizi dan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun demikian, sekitar 90% kebutuhan kedelai dipenuhi dari impor. Bahkan, kebutuhan impor kedelai dari tahun ketahun pun semakin meningkat. Padahal, Indonesia pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1984, 1985, dan 1992 dimana kebutuhan lokal dapat dipenuhi dari lahan produksi dalam negeri. Saat ini, kebutuhan kedelai setiap tahun di kisaran 3.6 juta ton, produksi kedelai nasional pada tahun lalu di kisaran 340.000 ton, setara dengan kurang lebih 10% dari pemenuhan tingkat kebutuhan.
Ketersediaan Kedelai Nasional dan Industri Pengolahan Kedelai
- Atris
- Category: Artikel
- Hits: 361
Pengembangan Kedelai Nasional
Pengembangan ketersediaan kedelai lokal bagi industri dan pengrajin olahan kedelai diperlukan dalam rangka mempersiapkan kedaulatan pangan dan program swasembada kedelai Nasional oleh Pemerintah ditahun 2018. Tanpa disadari sejak tahun 1984 kebutuhan kedelai Nasional dikarenakan permintaan akan kedelai untuk bahan baku pangan di Indonesia yang terutama industri tempe dan tahu yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dipenuhi dari kedelai import.
Kedelai import yang dikirim ke Indonesia dari Amaerika sebagian besar sampai di pengrajin sudah tidak segar lagi, tersimpan lama digudang dan bersifat trasngenik ( GMO /Genetically Modified Organism). Sementara kedelai lokal memiliki berbagai keunggulan sebagai komoditi masyarakat petani dibandingkan dengan kedelai import dikarenakan kedelai lokal lebih fresh, lebih murni bersifat non modifikasi genetik/trasngenik, memiliki mutu dan nilai gizi yang lebih baik, dan memiliki rasa dan aroma yang lebih baik. Kedelai lokal juga memiliki keunggulan aspek budidaya yang lebih baik dan ukuran butir biji pada beberapa varietas unggul seperti varietas baluran dan grobogan lebih besar dibanding kedelai import. Rata rata mencapai berat sebesar 117gr / 100 biji, sementara kedelai import hanya sebesar rata rata 114 gr/100 biji.
Hal yang Belum Banyak diketahui Kita-Kita, Keunggulan Kedelai Petani Indonesia
- Atris
- Category: Artikel
- Hits: 393
Kebutuhan Kedelai
Kebutuhan kedelai dalam negeri di Indonesia sebagian besar mencapai 95% tahun ini dipenuhi dari Kedelai import sebagian besar dari USA yang berjenis GMO (Rekayasa Genetik). Harga kedelai dipasaran supermarket saat ini utk kedelai hitam petani sebesar Rp 22.000 hingga Rp 24.000. Demkian juga Kacang Hijau, sebesar Rp 20.000 sd 24.000. Kedelai hitam dan Kacang hijau yang ditanam petani jenisnya murni non GMO. Sementara Harga Kedelai Import GMO sebesar Rp 9.600 ditingkat pengrajin tahu tempe, di Kopti oleh Importir diberikan Harga dikisaran Rp 8.400 sd 8.600.
Kedelai kuning yang ditanam petani jenis murni Non GMO saat inipun dihargai sama bahkan lebih rendah dengan harga kedelai import sebesar kurang dari Rp 9.600. Untuk dipergunakan menjadi bahan baku tempe dan tahu, masyarakat dan pengrajin masih cenderung tidak dapat membedakan kedelai kuning GMO dan Non GMO ini. Hal inipun kini berdampak, harga kedelai kuning hasil panen yang jenisnya non GMO dipasaran dijual petani dan dibeli pengrajin tahu dan tempe dengan harga murah sebesar Rp 9.600. Sementara kedelai hitam dan kacang hijau dihargai cukup tinggi dipasar Rp 22.000 sd 24.000.
Peneliti Kedelai UGM yang Bersungguh-sungguh Memberdayakan Petani Kedelai Lokal
- Administrator
- Category: Artikel
- Hits: 374
Sumber Kagama (20 Juli 2020). Dr. Atris Suyantohadi, STP, MT dilahirkan di Grobogan, 6 September 1968. Pendidikan SD dan SMP ia tempuh di kampung kelahirannya. Selepas lulus SMP tahun 1985 Atris meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Tamat SMA tahun 1988 ia mendaftar masuk PTN dan diterima di Sastra Inggris UNS Surakarta. Namun Atris sadar bahwa ia kuliah bukan di bidang ilmu yang menjadi passionnya. Akhirnya pada tahun 1989 ia ikut ujian masuk PTN lagi dan ia sangat bersyukur berhasil diterima di fakultas yang diidamkannya yaitu Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Sekedar informasi, dunia pertanian telah menjadi kesehariannya semenjak kecil, karena ia dilahirkan di daerah sentra penghasil kedelai dan jagung.
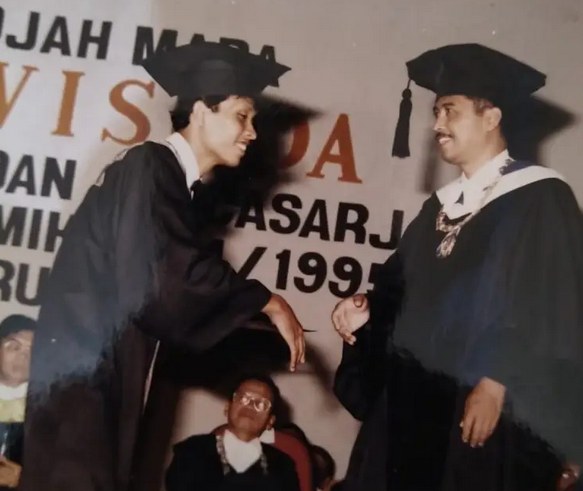
Sewaktu kuliah Atris lebih fokus ke studinya yaitu banyak belajar & berkutat dengan praktikum di lab. Sesekali ia ikut berkegiatan di HIMATIPA (Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Pertanian) dan sambil bekerja paruh waktu sebagai instruktur di Lembaga Manajemen Komputer, Yogyakarta. Dengan tidak banyak mengalami hambatan selama kuliah, akhirnya pada bulan Februari 1995 Atris berhasil meraih gelar S1-nya.
Tidak butuh waktu lama buat Atris mendapatkan pekerjaannya. Karena terbiasa menjadi asisten dosen yang tugasnya membantu pekerjaan di laboratorium, begitu selesai wisuda ia diterima sebagai dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Informasika dan Komputer Dian Nuswantoro, Semarang. Pada tahun 1996 saat ada informasi lowongan staf pengajar di lingkungan FTP, Atris diminta dosen seniornya mendaftar dan diterima menjadi dosen dengan status CPNS. Tidak lama kemudian, pada tahun 1997 SK pengangkatannya menjadi PNS turun. Sejak saat itulah karirnya menjadi dosen tetap di FTP dimulai.

Untuk mendukung karirnya pada tahun 1999 Atris memutuskan melanjutkan studinya. Karena basicnya bekerja dengan komputer di lab Analisa Sistem dan Simulasi Departemen TIP FTP, ia memilih kuliah di Jurusan Elektro Fakultas Teknik UGM dengan fokus mempelajari Sistem Komputer dan Informasi yang diaplikasikan dibidang teknologi pertanian. Pada tahun 2002 ia berhasil merengkuh gelar S2-nya.
Enam tahun kemudian Atris kembali melanjutkan jenjang studinya. Kali ini ia mengambil gelar S3 di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Hanya butuh dua setengah tahun baginya untuk mendapatkan gelar S3-nya. Tahun 2010 ia resmi menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude.

Atris tidak menyangka disertasinya yang menerapkan artificial life dengan kecerdasan sistem untuk optimasi budidaya kedelai, akan mengubah takdir hidupnya menjadi seorang peneliti kedelai dan setiap hari akan berkutat dengan masalah kedelai beserta varian produk olahannya. Saat menjadikan kedelai lokal sebagai obyek disertasinya, Atris lama-lama paham dilematis dilema perkedelaian di Indonesia. Minat petani untuk menanam kedelai lokal kurang begitu tinggi, daerah–daerah sentra kedelai makin menyusut, akibatnya produksi menurun drastis dari tahun ke tahun. Seperti ia saksikan sendiri di tanah kelahirannya Grobogan, bagaimana lahan untuk bertanam kedelai semakin menyusut secara tajam. Sehingga di tahun 2014, Atris bersama dengan Bupati Grobogan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab, Grobogan, sampai menggagas pendirian Rumah Kedelai Grobogan (RKG) untuk memunculkan kedelai lokal sebagai produk unggulan daerah kabupaten.

Atris masih ingat betul di tahun 1982-1984 saat negara kita berhasil dengan swasembada pangannya, termasuk padi dan kedelai. Tidak ada impor menyebabkab harga kedelai tinggi. Saat itu animo petani menanam kedelai sangat tinggi, karena nilai tukar 1 kg kedelai setara dengan 2 kg beras. Kebutuhan kedelai secara nasional telah tercukupi tanpa perlu impor. Jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini, di mana kebutuhan kedelai nasional menurut data terbartu tercatat 3,8 juta ton / tahun sedangkan produksi kedelai lokal hanya berkisar 800 – 900 ribu ton / tahun. Artinya, hampir 80% kebutuhan kedelai kita baik untuk diproduksi & konsumsi ada ketergantungan kepada kedelai impor, dan mayoritas termasuk jenis GMO (Genetically Modified Organism) atau hasil rekayasa genetika.
Melihat fenomena tersebut timbul kerisauan dalam hati Atris. Kepeduliannya tumbuh, rasanya harus ada gerakan atau sosialisasi dalam skala masif untuk lebih memperkenalkan kedelai lokal kepada petani dan masyarakat. Sayang sekali, kita punya banyak kedelai varietas unggulan lokal yang sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan kedelai impor, sebut saja varietas Anjasmoro, Grobogan, Agromulyo, Wilis, Burangrang, Biosoy dll. Namun yang terjadi para petani dan masyarakat masih memandang rendah, dalam benak mereka tertanam keyakinan bahwa kedelai lokal itu kecil-kecil, banyak kotoran dan tidak bagus dibuat tempe.

Atris percaya keyakinan itu bisa diubah, meski ia sadar akan butuh waktu lama dan tidak bisa dikerjakan sendirian. Akhir tahun 2014 dimulailah misi untuk meningkatkan value added kedelai lokal melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung dari fakultas dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM) UGM. Pelan-pelan ia menjalin hubungan baik dengan para petani kedelai di daerah sentra kedelai seputaran Jawa Tengah – DIY seperti Grobogan, Pati, Sukoharjo, Sleman dan Kulonprogo. Ia juga melakukan pembinaan intensif kepada UMKM di wilayah tersebut dengan melakukan pendekatan lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan value kedelai menjadi produk–produk olahannya.
Berbagai upaya dilakukan Atris dalam mewujudkan misinya tersebut. Di antaranya adalah memperkenalkan kepada UMKM produk olahan berbahan kedelai lokal yang lebih healthy, serta mengajarkan mengolahnya menjadi berbagai varian produk seperti tempe, tahu, susu kedelai, soyghurt, dll. Untuk petani binaan Atris berupaya membantu dari hulu ke hilir, dari pengadaan bibit yang asalnya dari pemerintah sampai mengusahakan hasil panen petani dibeli dengan harga yang pantas. Kemudian Atris juga berusaha menjembatani para petani dengan dunia industri. Yang telah terjalin komunikasi salah satunya dengan perusahaan snack sehat Soyjoy dan Nestle dengan produknya bubur bayi berbahan kedelai non-GMO.

Tahun 2014 terjadi sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh Atris. Pada sebuah acara kampus Fakultas Teknologi Pertanian, UGM, ia bertemu narasumber pengisi acara yang bernama Rustono seorang pemuda asal Grobogan yang sukses besar menjadi pengusaha tempe di Jepang. Kebetulan Rustono adalah kakak kelas Atris saat di bangku SMP dulu. Pertemuan itu berlanjut saat ada tugas ke Jepang, Atris mengunjungi rumah Rustono di daerah Shiga, Kyoto.
Di Jepang Rustono menceritakan seluk beluk bisnisnya dari hulu ke hilir. Yang membuat Atris kagum adalah bagaimana pola kemitraan yang dijalin Rustono dengan petani kedelai di Jepang. Meski lahan di Jepang tidak seluas di Indonesia, namun produksi tempe Rustono tidak menggunakan kedelai impor. Berkat menjalin kemitraan yang bagus, kebutuhan kedelai sudah bisa tercukupi oleh petani lokal. Atris berpikir hal itu sangat menginspirasi. Sistem demikian ini akan banyak membantu petani lokal untuk diterapkan di Indonesia.

Terinspirasi dari Rustono, pada tahun 2015 Atris mendukung istrinya mendirikan perusahaan pengolah kedelai lokal non-GMO dengan merk dagang “Attempe”. Produknya berupa tempe segar dalam berbagai kemasan, kripik tempe dan tempe instan. Di perusahaan tersebut Atris menerapkan pola kemitraan dengan petani kedelai yang sama-sama saling menguntungkan. Saat ini pabriknya mampu memproduksi kedelai dengan berbagai produk tempe dan turunannya untuk dikomersialisasikan ke masyarakat berbahan baku 100% kedelai lokal.
Segala daya upaya yang telah dimulai Atris sejak 10 tahun yang lalu, di mana 5 tahun terakhir sangat intensif, menurut Atris perlahan mulai terasa pengaruhnya. Wacana yang berkembang di pedesaan khususnya bagi para petani dan masyarakat mulai menyadari kedelai lokal tidak serendah yang dibayangkan, bahkan sebaliknya lebih berkualitas dan menyehatkan. Ditambah dengan pola kemitraan yang dibangun secara jelas dan ada jaminan hasil panen langsung terserap pasar, dampaknya membuat petani semakin banyak yang tertarik menanamnya. Untuk UMKM binaan sudah tumbuh kembali kebiasaan mengolah produk berupa tahu dan tempe berbahan baku kedelai lokal.

Selain melakukan pembinaan intensif kepada petani dan UMKM, Atris juga masih terus melakukan penelitian dan inovasi terhadap kedelai lokal berdasar ilmu yang dikuasainya. Ia secara kontinyu terus mengembangkan kedelai dengan kecerdasan sistem untuk optimasi pertumbuhan. Selain itu ia juga mengembangkan inovasi produk-produk olahan kedelai seperti tempe instan dan tempe spirulina yang memiliki kandungan tinggi aktifitas antioksidan untuk pencegahan dan pengobatan kanker. Semua itu didukung oleh pengetahuan yang sangat mumpuni tentang aspek higienitas proses produksi serta mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. “Saat ini, kami mengembangkan tempe siap saji (ready to eat) dalam bentuk kaleng untuk memenuhi masyarakat Indonesia di luar negeri yang menginginkan tempe di sana.” kata Atris.
Atris merasa cukup puas atas pencapaiannya selama ini, namun ke depannya ia masih menyimpan harapan dan impian yang banyak. Satu yang terpenting, pemerintah harus mendukung sepenuhnya dalam menjembatani pemberdayaan petani kedelai dari hulu ke hilir jangan sampai terputus. Petani jangan sampai kesulitan dalam mendapatkan benih dan sarana produksi, lalu saat panen raya harga jangan sampai terlalu anjlok dan kalau bisa hampir semuanya terserap pasar.

Mengenai daerah binaannya yang hanya seputar wilayah DIY – Jateng saja, Atris mengatakan “Ini berkaitan dengan tenaga dan waktu yang kita miliki. Inginnya kita bisa mencakup wilayah yang lebih luas lagi, namun semua itu terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada.”
“Yang terpenting adalah paling tidak kita sudah melakukan upaya mengangkat derajat kedelai lokal dan itu sudah terasa pengaruhnya. Petani-petani mulai semakin mengenal kedelai varietas lokal dan semakin tinggi animo menanamnya. Jika bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi iya kan?” demikian ungkap Atris.
Viral Tempe Kedelai Kuning Lebih Baik dari Tempe Kedelai Putih, Benarkah?
- Administrator
- Category: Artikel
- Hits: 431
Sumber: KOMPAS.com - Sebuah unggahan di Facebook viral di media sosial menyebutkan tempe berwarna kuning lebih baik dibandingkan tempe dengan kedelai berwarna putih. Menurut informasi viral itu, tempe dengan kedelai berwarna putih merupakan kedelai GMO (Genetically Modified Organism) atau transgenik. Kandungannya dianggap dapat menimbulkan penyakit tertentu. Unggahan tersebut disertai foto tempe dengan kedelai kuning dan putih.
Tanggapan Ahli
Peneliti Kedelai Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Atris Suyantohadi mengatakan, di Indonesia memang terdapat kedelai lokal dan kedelai impor.
"Kedelai lokal Indonesia yang ditanam petani itu rata-rata kedelai yang berwarna kuning. Tapi ada juga kedelai hitam yang sering dipakai untuk kecap," kata Atris saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/12/2019). Atris menjelaskan, produksi tempe di Indonesia juga menggunakan kedelai lokal dan impor. Menurut dia, kedelai lokal juga tidak selalu berwarna kuning setelah diproses menjadi tempe. "Kalau menggunakan kedelai lokal, kedelai varietas kuning diolah menjadi tempe bisa jadi warnanya hampir sama. Tapi, tidak terus menunjukkan kedelai lokal warnanya kuning, kedelai impor warnanya putih. Tidak," ujar Atris.
Uji laboratorium, lanjut Atris, menunjukkan bahwa kedelai lokal tidak mengalami modifikasi rekayasa genetik. Sementara itu, kedelai impor terdiri dari dua jenis, yaitu non-modifikasi rekayasa genetik (murni) dan kedelai transgenik atau mengalami modifikasi rekayasa genetik. "Dari sisi harga, dua jenis kedelai ini beda. Kedelai transgenik lebih murah dibandingkan kedelai non-transgenik," kata Atris.
Dengan alasan harganya yang lebih murah, maka kedelai transgenik diimpor ke Indonesia. Sementara, kedelai non-transgenik diimpor perusahaan-perusahaan tertentu yang memang konsen menggunakan bahan organik.
Membedakan Tempe dari Kedelai Lokal dan Impor
Atris memaparkan, dari sisi tampilan, tempe dari kedelai lokal dan impor sulit dibedakan. Meski demikian, tempe dari kedelai lokal dan impor dapat dibedakan dari segi rasa. "Sisi rasa bisa untuk parameter membedakanya. Tempe kedelai lokal terasa lebih kuat rasa kedelainya, lebih gurih rasa kedelainya dan juga lebih fresh," papar Atris. "Jika dari penampakan, agak sulit untuk membedakan tempe kedelai lokal atau tempe kedelai impor. Kecuali yang terlatih.jika ingin kepastian lebih detail, dengan uji laboratorium," lanjut dia.
Meski petani memproduksi kedelai lokal, kedelai impor mendominasi pasar di Indonesia. Atris memaparkan, meski belum ditemukan kasus bahwa kedelai transgenik menyebabkan penyakit tertentu, produk transgenik atau yang mengalami rekayasa unsur pangan dalam jangka waktu panjang dapat memicu munculnya penyakit karsinogenik seperti tumor, miyom, dan kanker. "Mungkin bukan transgenik semata, tapi bisa sebagai memicu," kata dia.
Penyakit karsinogenik di Indonesia memang semakin meningkat volumenya. Oleh karena itu, selain untuk mendukung petani, menggunakan tempe berbahan kedelai lokal juga diklaim lebih baik.
Pelabelan Pangan
Menilik aturannya, pemerintah telah mengatur produsen untuk memberikan label bagi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetika.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 35 PP Nomor 69 Tahun 1999 ini berbunyi:
- Pada Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan "PANGAN REKAYASA GENETIKA".
- Dalam hal pangan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalan suatu produk pangan, pada label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja.
- Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.
Page 1 of 2